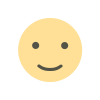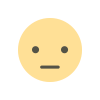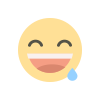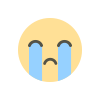Demo 25 Agustus: Alarm Publik untuk DPR dan Elite Politik
Demo 25 Agustus jadi tanda ketidakpuasan rakyat terhadap DPR. Krisis kepercayaan ini peringatan serius bagi elite politik agar tidak abai pada rakyat.

Demonstrasi yang terjadi pada 25 Agustus di depan Gedung DPR kembali menjadi sorotan publik. Aksi tersebut tidak hanya menandai ekspresi ketidakpuasan masyarakat, tetapi juga mencerminkan semakin lebarnya jurang antara rakyat dan para wakilnya di parlemen.
Gelombang protes itu muncul di tengah situasi ekonomi yang sulit. Masyarakat masih dibayangi harga kebutuhan pokok yang tinggi, lapangan pekerjaan yang semakin sempit, serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Namun, di saat yang sama, publik dikejutkan dengan kabar mengenai peningkatan tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR.
Kesenjangan inilah yang menjadi bahan bakar utama di balik demonstrasi. Bagi masyarakat, keputusan politik yang lebih mementingkan kenyamanan elite ketimbang kebutuhan dasar rakyat jelas sulit diterima. Aksi massa 25 Agustus bisa dibaca sebagai bentuk “alarm” dari publik bahwa kesabaran mereka kian menipis.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Setiap kali keputusan elite politik dianggap tidak berpihak pada rakyat, jalanan selalu menjadi ruang alternatif untuk menyampaikan aspirasi. Ketika saluran formal dianggap tidak efektif, suara rakyat menggelegar di jalan-jalan ibu kota.
Yang perlu dicatat, aksi demonstrasi bukanlah sekadar kerumunan penuh emosi. Ia adalah sinyal politik. Ketika masyarakat memilih turun ke jalan, itu menandakan ada krisis kepercayaan yang serius terhadap lembaga perwakilan. DPR, sebagai institusi yang seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, justru dianggap semakin jauh dari realitas kehidupan sehari-hari konstituennya.
Kekecewaan publik yang terekam dalam demonstrasi 25 Agustus seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para pemegang kekuasaan. Alih-alih merespons dengan defensif atau mencari pembenaran, DPR dan elite politik harus membuka ruang dialog yang lebih nyata, transparan, dan substantif dengan masyarakat.
Sebab, bila jurang ketidakpercayaan ini terus melebar, konsekuensinya tidak hanya soal citra buruk di mata rakyat, melainkan juga mengancam legitimasi politik itu sendiri. Demokrasi kehilangan maknanya ketika wakil rakyat gagal menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan negara.
Aksi 25 Agustus adalah pengingat keras bahwa rakyat tidak tinggal diam. Mereka masih memiliki suara, baik di jalanan maupun di bilik suara. Pertanyaannya, apakah elite politik mau mendengar sebelum semuanya terlambat?